TRAVEL
5/Travel/post-list
POPULER
Tertawalah Sebelum Mereka Bubar
Jumat, Mei 25, 2007
Obsesi Penjual Ginjal
Jumat, Februari 09, 2007
Bercengkrama Dengan Mayat
Kamis, Februari 01, 2007
SOSOK
4/Sosok/post-list
Suatu Siang di Macao Pao
Rusman Manyu
Senin, Mei 21, 2007
 |
Kian siang kawasan itu kian ramai. Ojek. Bajaj. Kendaraan roda empat. Semua hilir-mudik. Riuh. Pedagang kaki lima yang menjual rokok, tukang sol sepatu, dan gerobak buah-buahan, ikut melengkapi daerah berjuluk ‘kota tua’ tersebut.
Bisa dipahami keriuhan macam itu. Selain menjadi perhentian terakhir kereta api di pusat kota Jakarta, stasiun itu dekat juga dengan kawasan pertokoan dan pusat bisnis lainnya. Tak jauh dari stasiun, terlihat megah Museum Bank Mandiri dan gedung-gedung lain yang usianya sudah tak muda lagi.
Dua orang perempuan berdiri di pintu sebuah rumah yang bagian depannya terbuat dari papan, dan berada di seberang stasiun. Seorang di antaranya sudah berumur. Dandanannya alakadarnya. Antingnya berupa sepuhan emas sebesar pergelangan tangan. Ia memakai kaos ketat berwarna merah. Bulu ketiaknya terlihat jelas. Celana katun pendek berwarna hijau memperlihatkan bagian paha yang tak sedap dipandang mata. Berkeriput.
Satunya lagi, yang lebih muda, juga berbusana tak karu-karuan. Berbaju kerah cokelat dengan celana panjang warna abu-abu, dia lebih banyak diam. Rambutnya panjang tapi terlihat kusut. Mereka jauh dari kesan cantik. Banyak melamun dan hanya sesekali berbicara. Mata mereka terlihat sembab.
“Mampir, Mas!” ajak perempuan berwajah tua kepada seorang lelaki yang melintas.
***
Saya berdiri tak jauh dari mereka, namun sapaan itu terdengar jelas. Pikiran kotor langsung menerawang. Rada aneh saja. Bayangkan, ada perempuan yang menawarkan ‘mampir’ saat lelaki melintas di siang hari.
“Motornya parkirin di sini saja. Entar hilang loh,” ujar perempuan tua itu. Si perempuan muda cemberut.
“Emangnya lagi ngapaian, Mas?” tanyanya.
“Mas, minta rokoknya,” celetuk perempuan yang banyak diam itu.
Saya menyodorkan bungkus rokok dan koreknya. Dia mengambil sebatang dan langsung dinyalakan. Diisapnya kuat-kuat sampai terlihat kedua pipinya mengempot. Buzz...buzz....asapnya diembuskan. Ia terlihat cuek dan tak terdengar kata-kata terima kasih darinya.
“Mas, lagi ngapain sih. Dari tadi berdiri aja. Mau pasang bom ya?” tanya perempuan STW alias setengah tua itu. “Kenalin nih, teman saya. Namanya Ijah,” dia menyebut nama perempuan muda itu. “Masih montok, 26 tahun.” Ijah menyikutkan tangan kirinya ke tubuh perempuan tua itu. “Tuh ada cowok muda, mau nggak lu.” Ledeknya ke Ijah. “Ogah,” jawabnya.
“Lagi lihat-lihat gedung tua aja, Mbak.” Saya menjawab.
Ijah masuk ke dalam rumah dengan memperlihatkan mukanya yang tak sedap dipandang mata, mencibir. Tak lama kemudian, perempuan tua itu juga masuk sambil menutup pintu.
Saya menyeberang jalan ke arah depan stasiun sambil mendekati seorang ojek sepeda motor. Lelaki ini bernama Bejo. Usianya 28 tahun. Sudah dua tahun dia mangkal di Jembatan Batu. Dia hapal wilayah itu. Dari setiap lorong, tempat wisata, sampai tempat mangkal perempuan pekerja seks.
Secara diam-diam, dia juga kerap memberikan petunjuk bagi lelaki yang ingin menyalurkan syahwat. Perempuan yang di seberang stasiun Beos, kata dia, bukan hal aneh lagi. Tidak seperti di lokalisasi, mereka bekerja dan mencari pria hidung belang tanpa mucikari alias freelance.
“Emangnya mau main sama yang tua, Mas,” tanya dia. Saya tertawa. “Mas, di sini masih banyak yang muda, cantik dan lebih bersih. Yang Chinese juga banyak.”
“Yang di depan itu berapaan,” tanya saya. Maksudnya, perempuan yang tadi saya jumpai.
“Paling juga Rp50 ribu. Soal tempat, mereka punya. Bisa di dalam rumah itu. Bisa juga di tempat lain,”katanya, mencoba menerangkan. “Paling mahal Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Itu udeh ama tempat.”
Dia menunjuk tempat yang bisa digunakan untuk berkencan. Sebuah gedung tua yang bersebelahan dengan warung telekomunikasi alias wartel Perkasa. Walaupun tak memiliki plang nama, namun Bejo menyebutnya hotel. Tak ada tanda-tanda sebagai tempat penginapan. Dari depan, justru terlihat seperti bengkel mobil.
“Itu namanya hotel Horas. Kadang juga disebut Pasundan. Yang punya, orang Batak,” ujar Bejo. Batak adalah sebutan suku di Sumatera Utara. Nama ‘Horas’ itu ternyata terpasang di bagian kiri gedung yang berukuran kecil. Sekilas tak akan ada orang yang memperhatikannya.
Bejo menceritakan, biasanya setiap malam minggu penginapan itu ramai. Banyak perempuan yang mangkal di dalamnya. Ada juga perempuan yang dibawa dari luar. Di tempat itu juga tersedia. Biasanya, mereka memang punya kamar sendiri. “Banyak juga yang masih muda-muda,” ujarnya.
Dia menjadi jasa omprengan hidung belang. Sebagai tukang ojek, penghasilannya tidak terpenuhi untuk hidup. Hari itu saja, sejak pagi hingga siang hari, baru mendapatkan uang Rp10 ribu. Mengojek dan menawarkan perempuan, menurutnya, pekerjaan yang sulit dipisahkan.
Lumayan pendapatannya. Dari perempuannya, katanya, ia mendapatkan tip lima ribu. Sedangkan dari hidung belang ia memperoleh sepuluh ribu. Penghasilan di luar ojek, seharinya dikantongi bisa Rp50 ribu.
“Abisnya sekarang dapet duit susah, Mas. Daripada jadi penjahat beneran, mendingan jadi penjahat kelamin aja,” tuturnya sambil tertawa. “Mas, sampaikan kepada SBY, tolong dong orang miskin diperhatikan supaya kita tidak jadi penjahat terus.” SBY yang dimaksud adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
*****
Stasiun Jakarta Kota, dikenal dengan julukan Beos alias Bataviasezhe Oosterspoorweg Maatschappij yang diambil dari nama perusahaan kereta api pada saat itu. Stasiun ini kali pertama diresmikan pada 1929 di saat Jakarta, dulu Batavia, di bawah kekuasaan Belanda. Sedangkan lintasan rel kereta sudah dibangun sejak 1873. Lintasan inilah yang menghubungkan Beos ke seluruh pulau Jawa.
Setahun lamanya, stasiun ini dibangun dengan arsitek Ir. Frans Johan Louwrens Ghijsels, orang Belanda yang dilahirkan di Tulung Agung Jawa Timur pada 1882. Sosok alumni Delf ini akhirnya mendirikan biro arsitektur Algemeen Ingenieur Architectenbureau (AIA). Dia menjadi direkturnya.
Karya arsiteknya dianggap cukup terkemuka pada masa itu. Peninggalan yang terlihat saat ini, gedung Departemen Perhubungan Laut di Medan Merdeka Timur, gedung Bappenas di Jakarta, Rumah Sakit PELNI di Petamburan yang keduanya di Jakarta dan Rumah Sakit Panti Rapih di Yogyakarta.
Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jendral Jhr. A.C.D. de Graeff yang berkuasa di Hindia Belanda pada 1926-1931.
Stasiun Jakarta Kota dirancang berdasarkan perpaduan antara struktur dan teknik modern barat serta sentuhan bentuk tradisional setempat. Kelihatan artistik dengan balutan art deco yang kental. Rancangan ini kelihatan sederhana namun punya cita rasa tinggi.
Oleh pemerintah DKI Jakarta, Beos akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475 tahun 1993. Sayangnya, tak terawat. Dengan mudah masih ditemukan kerusakan kondisi bangunan. Namun, beberapa sudut keasliannya dipertahankan. Nuansa sebagai saksi bisu sejarah Jakarta, masih terasa.
Sejarah Jakarta Kota tak hanya pusat perdagangan dan tempat perputaran perekonomian negeri ini. Di abad 16 pada era VOC (Vereeniging Oost-Indische Compagnie), hanya berselang beberapa bulan J.P Coen mendirikan Batavia, kawasan itu sudah menjadi tempat pemuas nafsu kaum lelaki.
Alwi Shahab dalam artikelnya berjudul “Planet dan Mirasa Sky Club” menuliskan, hotel-hotel yang berada di depan Stasiun Jakarta Kota merupakan tempat konsentrasi pelacuran di Batavia. Julukannya, Macao Pao.
Nama itu diambil dari asal usul perempuan yang didatangkan dari Macao, salah satu wilayah daratan negeri China oleh jaringan germo Portugis dan China. Masa itu, tempat ini hanya khusus untuk melayani para pengusaha China dan petinggi VOC yang dikenal korup.
Kawasan itu sejak zaman penjajahan Belanda sudah dikenal sebagai komplek rumah bordil khusus kelas elit. Perempuannya didatangkan dari daratan Macao Pao, China. Orang Betawi menyebut mereka cabo, mengadaptasi dari kata dalam bahasa China, caibo atau simpanan. Orang Portugis menyebutnya Moler atau kupu-kupu malam.
Pelacur kelas bawah, yang tinggal tak jauh dari kawasan Macao Pao, berada di kawasan Glodok yang dikenal dengan “gang mangga”. Julukan ini bukan nama buah, melainkan nama penyakit kelamin perempuan atau yang dikenal sekarang dengan sebutan sipilis.
Kompleks pelacuran Gang Mangga kemudian tersaingi oleh rumah-rumah bordir yang didirikan orang China yang disebut soehian. Lokalisasi ini ditutup pada awal abad ke-20 karena sering terjadi keributan. Tapi kata soehian tidak pernah hilang dalam dialek Betawi untuk menunjukkan kata sial. Dasar suwean (sialan).
*****
Tak jauh dari rumah abu marga Tjong (Thio) yang tembok luarnya didominasi cat merah, duduk tiga perempun sambil makan nasi bungkus di balik kios kecil beretalase kaca. Dua perempuan berwajah cukup tua dan satu lagi masih terlihat muda. Bukan perempuan yang kali pertama saya temui. Mereka berdiri di atas trotoar.
Salah seorang yang berbadan gemuk, berwajah kusam, dan berpakaian tak rapi, mendekati saya. Ia menenteng sebotol minuman air putih. Dia berhenti dan air itu diteguknya. Batang kayu korek api, dicukil ke giginya. Saputangan di tangan kanannya, langsung dilapkan ke mulut. Dia bersendawa. Dengan cepat, telapak tangan menutup mulutnya.
“Mas, kayaknya capek. Mau dipijet nggak? Atau mau ngeseks? Murah aja kok,” tawarnya kepada saya.
Saya terdiam. Botol minuman air putih dari kios itu, saya teguk. Wanita ini tak menyerah menawarkan bisnis syahwatnya. “Cuma cepek,” ujarnya lagi. Cepek berarti Rp100 ribu.
“Nggak perlu bayar hotel lagi, Mas. Di kamar saya aja. Dekat kok, tuh di sana, cuma jalan kaki aja,” ujarnya. Telunjuknya mengarahkan tempat yang dimaksud untuk menjadi kamar kencan.
“Kurangin dong. Mahal banget,” saya menawar.
“Mas, itu cepek juga udeh murah. Sampe puas deh, terserah mau sampe jam berapa aja,” ujarnya. Tawaran itu saya iyakan. Dia berjalan terlebih dulu dan saya membututinya.
Saya membayangkan tempat itu nikmat untuk rebahan. Dengan tempat tidur yang empuk dan dengan pendingin ruangan yang sejuk. Apalagi dengan tarif yang super murah. Sudah pasti akan nyaman dengan ditemani seorang perempuan. Minimal bisa memijat dan tubuh menjadi relaks.
Dia sudah berada di sebuah rumah besar bertingkat tanpa plang nama. Dari luar terlihat seperti bengkel kendaraan. Di lantainya ada bekas ceceran oli. Tak ada lampu penerang. Ada dua motor yang parkir. Motor saya sandarkan di sebelah kamar yang yang berada bagian depan. Tempat itu yang ditunjukkan oleh Bejo, si pengojek sepeda motor.
Masuk ke bagian dalam, barulah terlihat banyak kamar. Sumpek dan kusam. Saya seperti masuk ke dalam sebuah lorong. Ada tiga lantai. Temboknya kotor dan tampak sudah tua. Ini terlihat dari banyaknya retakan bagian dinding dan tiangnya. Jemuran banyak bergantung di dekat pintu kamar.
Gila. Saya tersenyum sendiri menyaksikan kondisi bangunannya. Walaupun seperti penginapan, tapi saya merasakan masuk ke dalam gudang. Kondisinya memang lebih bersih dari pemukiman kumuh di Jatinegara. Terlihat perempuan menggendong anaknya sambil menjemur pakaian di lantai dua.
Dia membuka pintu salah satu kamar ketiga di sebelah kanan. Dari luar, pintu kamar ini sudah rusak. Saat buka pintu, bunyi mendecit. Ada jendela kaca nako bening berukuran setengah meter. Kacanya sudah tak utuh lagi. Hanya ditutupi kain yang sudah pudar warnanya.
Alamak. Kamarnya membuat saya terkesima. Hanya berukuran 3,5 x 3,5 meter. Kasur busa terhampar di atas lantai panggung setinggi 30 sentimeter. Kasur itu terlihat tak nyaman di mata. Kusam, bau, banyak bercak hitam, dan sprei yang sudah sobek-sobek serta berantakan.
Lampu kamar hanya lima watt. Tak ada kamar mandi. Ada ember hitam dan gayung di dekat kasur tadi. Untuk buang air, tempat itulah yang jadi alternatifnya. Jangankan lemari, tak ada tempat untuk gantung baju. Tak ada cahaya masuk. Angin yang masuk, justru semakin menebarkan aroma tak sedap.
Saya merebahkan badan. Wanita itu memperkenalkan diri tanpa jabat tangan. “Nama saya, Sri,” katanya. Usianya disebutkan, 41 tahun. Saya ganti nama menjadi Yanto.
***
Perempuan ini langsung membuka baju, celana panjang kain dan tali kutangnya. Badannya terlihat gempar. Bahkan daging bagian perutnya terlihat sesak, terjepit celana dalam yang masih dikenakan.
Dia meminta saya melepas pakaiannya. Saya menolak. “Kita ngobrol aja. Sambil ngobrol, mbak bisa pijetin kaki saya. Kali aja saya bisa tertidur,” bujuk saya. Dia mengiyakan.
“Saya bersih, Mas. Rajin periksa. Kalau mau pakai kondom, pakai aja. Tapi saya nggak bawa. Lagian kalo pake kondom, entar nggak suka lagi,” tuturnya. Saya tetap menolaknya.
Yang saya pikirkan adalah ketakutan terkena penyakit kelamin. Saya tidak yakin, perempuan ini bersih dari penyakit. Apalagi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta kian lama kian tinggi, ribuan penderitanya. Penyakit ini sudah pasti mudah menyerangnya. “Saya mencintai pacar saya. Masih punya masa depan,” pikir saya.
Sambil memijat, dia bercerita tentang perkawinannya. Dia bercerai dengan suami pertamanya 20 tahun lalu. Dia butuh uang untuk membiayai ketiga anaknya. Pernah menjadi tukang cuci baju tetangga, sampai jualan rokok di pinggir jalan. Berbagai pekerjaan yang dicobanya itu ternyata tak banyak menghasilkan uang.
Akhirnya, atas ajakan seorang temannya, dia tergiur untuk bekerja sebagai pelayan karaoke di Mangga Besar, Jakarta Pusat. “Gue kan tinggalnya di Tangerang. Akhirnya enakan cari kosan aja. Patungan ama temen,” tuturnya.
Sebagai pelayan karaoke, honor yang diperoleh tak memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat itu, sebulan hanya mendapatkan upah Rp75 ribu. Lagi-lagi, dia tergiur dengan temannya yang kelihatannya sudah mapan. Ternyata, selain bekerja sebagai pelayan karaoke, juga nyambi menjadi PSK. “Saya bayangin, setiap malam dapat duit Rp100 ribu,” tuturnya.
Sri terlihat kepanasan. Baju yang diletakkan di samping ranjang, diambil dan diusapkan ke wajahnya. Dia membuka kain jendela. Lampu kamar dimatikan. Angin baru terasa masuk ke ruangan. Saya lega. Sekian waktu, saya menahan rasa panas. Cahaya dari luar, lebih terang dibandingkan dari lampu yang remang itu.
“Saya ini dulu menjadi primadona, Mas. Waktu itu kan masih muda. Sekarang aja udeh tua. Dulu, semalam bisa saya layani empat sampai lima laki-laki.” Dia tertawa kecil sambil terus mengusap keringat di badannya. Bugil.
“Dulu sih, tarif gue bisa Rp300 ribu. Uang segitu, saat itu udeh tergolong paling mahal. Karena sekarang udeh tua gini, maka harganya juga kendor,” ujarnya. Kendor dimaksud adalah murah.
Kejayaan sebagai primadona itu, sirna. Dia terpaksa memasang tarif murah. Karena usianya yang tua, susah memasang tarif mahal. Namun dia tetap harus mencari uang untuk makan. Pasang tarif Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. “Sekarang anak-anak udah pada besar dan bisa cari duit sendiri. Jadi, duit yang saya peroleh untuk makan sendiri.”
Dia beruntung, pemilik Pemondokan Horas tidak mengenakan tarif sewa kamar. Hanya sekedarnya saja, setiap bulan dia harus membayar jasa kamarnya. Kadang sebulan hanya Rp100 ribu.
Hari menjelang sore. Di tempat itu, saya tidak bisa tidur dan badan terasa gatal. Dia meminta sebatang rokok. Embusannya cukup kuat sampai mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Saya juga mengisap rokok agar aroma kamar lebih terasa bau rokok dibandingkan pengap dan amis.
Pakaian yang terhambur di kasur kusam, dikenakan. Saat mengenakan celana panjangnya, terlihat sulit. Dia harus menarik napas agar perutnya bisa menyusut. Namun, perutnya tetap terjepit dan sebagian dagingnya menyembur dari atas celananya.
Saya menyerahkan uang Rp100 ribu. Dia masukkan ke dalam kantung celana kanannya. Dia membuka pintu. Tetap saja mendecit. Napas saya lega, bisa keluar dari ruangan yang sulit untuk bernapas. Dua anak kecil berlari di depan pintu kamar.
Dari usia muda sampai tua, profesi itu tetap dilakukan. Dari pasang tarif mahal sampai murahan. Kesendirian hidup selalu ditemani keringat untuk mendapatkan uang. Usia Sri dan Stasiun Kereta Beos, terus berpacu semakin tua dan sulit untuk berakhir.
Catatan: Foto diambil dari situs jejakpiknik
Reactions
Anda mungkin menyukai postingan ini
POPULER
Obsesi Penjual Ginjal
Jumat, Februari 09, 2007
Apa Kabar God Bless?
Senin, Juli 30, 2007
Tertawalah Sebelum Mereka Bubar
Jumat, Mei 25, 2007
PILIHAN
3/random/post-list

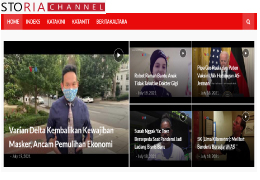





4 Komentar
Disinilah tempatnya.
1. Penginapan Bayu Murti
2. Penginapan Gaviota.
Adapun fasilitasnya : tv 21", wellcome drink n snack, kmr mandi dalam, parkir luas, tempat aman dan nyaman.
Tarif Rp 40rb+tv (2 orang),
Tarif Rp 50rb family, dan
Tarif Rp 25rb-tv.
Berminat? Untuk info lebih lanjut silahkan
hubungi : Rosyid
085643644446,
02744464446.
Email: techpyex@gmail.com Terima kasih.