TRAVEL
POPULER
Tertawalah Sebelum Mereka Bubar
Obsesi Penjual Ginjal
Bercengkrama Dengan Mayat
SOSOK
Hidup Tak Semanis Air Tebu

Batangan tebu yang sudah dikelik dimasukan ke mesin pemutar. Hasilnya, tetesan sari tebu menetes dan tertampung di baskom berisi batu es yang diletakkan di bawah mesin pemeras. Proses itu berulang kali dilakukan sampai batang tebu tak lagi mengeluarkan sari manisnya.
Kemudian, sari tebu itu dituangkan ke sebuah kotak minuman berukuran 30x60 sentimeter yang disiapkan di atas meja dagangannya. Maka, sudah siap untuk diperdagangkan. Segelas dijual dengan harga Rp 2000. Rasanya manis dan dingin. Segar untuk dinikmati saat panas menyengat. “Manisnya dijamin tanpa ada tambahan gula,” tuturnya.
Begitu hari-hari Hasan sebagai seorang pedagang es tebu. Dagangannya berada di Jalan Tanah Mas 1, Jakarta Timur. Di atas trotoar yang sejuk di bawah pohon rindang, persis di depan sebuah bengkel taksi. Posisinya tak jauh dari bagian kiri arena pacuan kuda.
Banyak kendaraan yang singgah. Dari pejalan kaki, bersepedamotor, bahkan yang menggunakan mobil. Maklum saja, di Jakarta sudah sulit menemukan pedagang air tebu. Bahkan bisa tergolong langka. “Emang susah. Mungkin di Jakarta, cuma saya yang jualan es tebu,” ujarnya.
Soal perjalanan hidup, dia punya kisah yang akan terus membekas dalam dirinya.
Tahun 1970-an, Hasan meninggalkan kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat untuk berusaha di
Uang pengeluaran, tidak hanya untuk membayar perbaikan mobil atau menggaji supir. Namun, lebih banyak pengeluaran tak terduga. Hasan menyebutnya: uang aneh-aneh. Misalnya, bayar polisi kalau ditilang, bayar pungutan, bayar restribusi, salah sedikit bayar lagi, dan begitu seterusnya.
“Pokoknya, pengeluaran. Lebih banyak bayar pungutan daripada buat beli bensin atau masuk ke bengkel. Dikit-dikit, ditilang polisi. Terus, bayar retribusi yang bikin bingung,” tuturnya jengkel.
Tahun 1974-an, dia akhirnya mulai berdagang tebu. Banyak tempat yang sudah disinggahi. Dari kawasan Jakarta Kota, Manggarai, Monas, dan hampir seluruh penjuru Kota Jakarta pernah disinggahi. Dia sendiri yang mendorong gerobak, membeli batangan tebu, sampai menjualnya.
Saat maraknya aksi penembakan misterius yang dikenal dengan sebutan petrus di tahun 1980-an, Hasan agak ketakutan. Setiap hari dia khawatir kena sasaran. Dengan kondisi
Era itu,
“
Walaupun situasi menakutkan, tahun 1985 dia akhirnya menikahi seorang gadis sekampungnya bernama Fatmawati yang kini berusia 40 tahun. Selisih umur mereka 12 tahun. Untuk mereka, sebuah rumah petak berukuran luas 53 meter dibelinya di Jalan Balap Sepeda, Jakarta Timur. Saat itu dibeli dengan harga Rp 2 juta. Rumah itulah rumah pertama miliknya.
Dia bersyukur, hidup di
Rumah itu mempunya kenangan manis dalam hidupnya. Di situ ia membesarkan tiga anak gadisnya. Sayangnya, hanya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Anak gadis paling bungsu masih sekolah SLTA, yang kedua belum bekerja, dan anak pertamanya bekerja di supermarket.
Dapat membeli rumah, baginya tak sia-sia datang ke
Untuk bekerja di
Akhirnya, pilihan hidup sebagai pedagang air tebu sudah harga mati. Bahkan dia berkeinginan berdagang air tebu sampai akhir hayatnya. Dia tidak perduli bila malam hari untuk mengangkut tebu sendiri. Mendorong mesin pemeras tebunya dari rumah menuju lokasi jualannya sejauh 500 meter.
Intinya, kata dia, batangan tebu adalah sumber hidupnya. Dari tebu, bisa membeli rumah, bisa menikah, bisa menyekolahkan anak, dan memenuhi kehidupan. Yang terpenting, lanjutnya, tidak ada yang kelaparan walaupun penghasilannya pas-pasan dengan hidup sekadarnya.
Batangan tebu dikirimnya setiap malam yang ditumpuk di bawah rel kereta api kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Seorang warga Tionghoa, menjadi cukong tebu yang dikirim dari Tegal, Jawa Tengah. Hampir malam, Hasan membawanya berkarung-karung ke rumahnya di jalan Balap Sepeda, Rawamangun, Jakarta Timur.
Dia tidak pernah menghitung banyaknya batang tebu yang dihabiskan. Usai memerasnya, ampas tebu dikumpulkan di tempat sampah yang tersedia di belakang dagangannya. “Tapi, bayar sampahnya juga mahal. Di tempat lain, paling baying Rp 10.000. Kalau di sini, Rp 35.000 setiap bulannya,” ujarnya.
Hari sudah semakin siang dan panas kian menyengat. Istrinya datang membawa makanan dan ikut membantu menuangkan es tebu kepada pembeli. Hasan, tetap mengelik batang tebu. Mesin dinyalakan lagi. Sari tebu kembali tertampung. Digayungnya es tebu dan dituangkannya ke dalam gelas. Hasan meneguknya. Ia menikmati es tebu buatannya sendiri, yang jauh lebih manis dari hidupnya.

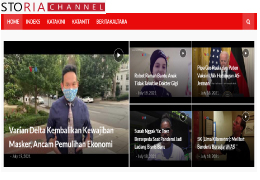





2 Komentar
Saya Iko di Tegal,Jateng. Saat ini di Tegal sedang menjamur penjual es tebu. Kebetulan saya sendiri sudah punya 3 cabang dan 3 mitra usaha.untuk Mesin dan pasokan tebu jangan kuatir, karena di daerah tegal dan sekitarnya saya yang yang memasok. Untuk Info Silahkan klik www.estebu.blogspot.com Berminat silahkan call ke 081334202895.
Terima kasih atas perhatiannya.
Hormat saya
iko
Silahkan mampir ke http://jatimegah.indonetwork.co.id/1414751/mesin-pres-tebupres-tebujuicer-tebugilingan-tebu.htm
Sedia pula suku cadang gearnya.
Terima kasih