TRAVEL
POPULER
Tertawalah Sebelum Mereka Bubar
Obsesi Penjual Ginjal
Bercengkrama Dengan Mayat
SOSOK
Andreas Harsono
Mencabut Kutukan
“Andreas Harsono,” ia menyebutkan namanya usai saya memperkenalkan nama terlebih dahulu.
Nama ini hanya saya kenal dari mulut yang sampai ke telinga saya dari kalangan mahasiswa dan wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu, saya masih status mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Kedatangan ke
Saya mewakili pers mahasiswa ‘suara manurung’ yang saya kelola dan diterbitkan atas nama Himpunan Mahasiswa Sastra
AJI dibentuk sebagai organisasi alternatif. Didirikan kali pertama di Sirnagalih tahun 1997. Kongres II yang rencananya diadakan di Puncak,
Andreas tidak ikut dalam kongres II, padahal ia juga dedengkot pembentukan AJI di Sirnagalih. “Tidak ada persoalan. Saya lebih memilih menulis saja di ISAI,” ujar dia, ketika saya tanyakan ketidakhadirannya. Usai Kongres II, saya ingin kembali ke
Dari stasiun Senen, kereta api kelas ekonomi memberangkatkan saya ke
Malam harinya, saya langsung menghubungi Andreas di nomor telepon rumahnya. Orang yang baru dua kali ditemui selama di
Esoknya, benar. Ia mengirimkan uang Rp150 ribu. Dengan uang itu, akhirnya saya bisa langsung naik pesawat untuk terbang ke
Tahun 1999, saya menemuinya lagi. Andreas sedang duduk santai di kursi besi di Kedai Tempo, Utan Kayu. Ia sedang ngobrol dengan Charles Dharapak, seorang fotografer asing. Saya diperkenalkan. Tak lama kemudian, datang Budiman Hartoyo, seorang jurnalis.
Yang saya simak dari perbincangan Andreas dan Budiman, tentang majalah pantau. Saya banyak diam. Maklum, tiga orang dihadapan saya, bukan orang jurnalis biasa. Apalagi, saya hanya pers mahasiswa. Budiman ditawari untuk menulis tentang Soeharto di majalah pantau. “mahluk apa pantau,” timbul dipikiran saya.
Saya mendengarkan perbicangan mereka. Andreas nampak serius. Kaca mata tak juga lepas dari hidungnya. Tampilannya sederhana. Mengenakan sandal jepit dan berpakaian kemeja.
Tahun 2001, dari
“Anda bisa liputan ke Palangkaraya, soal kerusuhan Sampit,” ujarnya, to the point. Saya menyatakan kesanggupannya.
Sepekan saya berada di Palangkaraya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Hubungan via telpon sering kami lakukan. Selain Andreas, Eriyanto juga kerap menelponnya. Bukan kerusuhan yang saya liput. Saya diminta menemui banyak media yang berkaitan dengan kerusuhan etnis di Sampit antara Dayak-Madura.
Dan itulah kali pertama saya menulis untuk majalah Pantau bersama Eriyanto. Orang yang dikenal sebagai riset media. Dan ketika itu pula, saya beberapa kali nulis di media watch itu. Mengisi rubrik sosok dan rubrik obrolah utan kayu. Inilah karier mula menjadi jurnalis. Sejak berada di negeri hutan itu, tak pernah menemuinya lagi. Palingan, via telepon atau email.
Tahun 2005, barulah saya bertemu lagi. Andreas saya undang ke Samarinda untuk membawakan materi diskusi jurnalisme. Tak hanya ia, ada Katamsi Ginano dari jurnalis pertambangan dan Meidytama dari The Jakarta Post.
“Saya membawa
“Silahkan mas, semua bisa diatur,”
“Tolong dong, nanti kamarnya yang bersih. Norman punya penyakit asma. Dia alergi dengan debu. Kalau bisa sebelum saya tiba, kamar udeh dibersihkan lagi,”
Saya kaget. Tapi harus saya lakukan. Pihak hotel Mesra Int, langsung saya hubungi untuk membersihkan kembali kamar yang akan ditempati Andreas dan anaknya. Ternyata, kedatangannya yang kali pertama ke Kalimantan Timur.
Di Samarinda,
Saya dan Andreas akhirnya banyak diskusi jurnalisme. Cara bicara dan temperamennya, ternyata tidak berubah sejak terakhir bertemunya di
Jurnalisme terakhir yang juluki, karena ia selalu mengatakan, media lokal harus merekrut orang asli. Dia menyinggung tentang koran Tribun Kaltim, anak media Kompas Group yang tidak merekrut orang Dayak. Ia rada marah ketika tahu Tribun Kaltim justru banyak melibatkan orang Jawa.
Saat konflik di Samarinda antara Dayak-Madura, Andreas juga telepon. Ia berada di NTT untuk menulis bukunya tentang Dari Sabang Sampai Merauke. Ia menceritakan adanya gerakan bawah tanah suku Dayak yang ingin merdeka. Ia tak hanya telepon, hampir setiap saat SMS-an.
Kini saya tinggal di
Ia sudah punya istri baru. Namanya Sapariah. Gadis berjilbab yang dibesarkan di

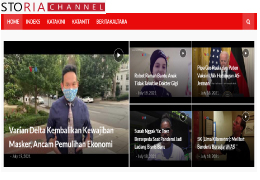





2 Komentar
sepertinya, sp sekarang, dari yang saya baca di blognya, persoalan Norman kian ruwet. apakah ini juga sejenis kutukan juga,he:)
Saya, Andreas, dan Norman, dan teman Pantau lainya, sering berenang sama-sama di apartemen Andreas. Dari suasana di kolam renang itu, Norman lebih tenang. Norman kadang polos menjawab kalau dirinya tidak menyukai ibu kandungnya. Aku berharap dari Sapariah yang sekarang menjadi istri Andreas, Norman bisa menemukan suasana keluarga kembali.